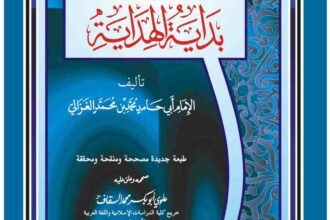Salah satu buku (kitab) legendaris dari dunia keilmuan Islam abad pertengahan, ialah karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah, sebuah buku panduan bagi para pencari ilmu—bukan sebagai kurikulum akademik, tetapi sebagai kompas spiritual. Kata-katanya yang padat makna menembus waktu dan batas geografis, tetap menyentuh pembaca masa kini yang dihadapkan pada pertanyaan yang lebih tua dari universitas itu sendiri: mengapa kita belajar?
Bagi Al-Ghazali, niat adalah segalanya, dan ilmu pengetahuan, jauh dari netral, bisa menjadi penyucian jiwa atau justru sumber kebinasaan. Dalam pandangannya, jalan seorang penuntut ilmu bukanlah mendaki menara gading atau mengejar ijazah—melainkan navigasi hati-hati antara tujuan, kekuasaan, dan kemurnian niat. Dan ia memperingatkan, bahaya bukan hanya ada dalam kebodohan, tetapi juga dalam ilmu yang menyesatkan.
Al-Ghazali menjabarkan lima motif dasar di balik pencarian ilmu, masing-masing sarat dengan bobot spiritual dan moral. Yang pertama, dan paling berbahaya, adalah mencari ilmu demi harta, status, atau pengaruh politik. Dalam model ini, belajar menjadi tindakan transaksional, pengetahuan dikomodifikasi untuk menaiki tangga duniawi, bukan tangga kebajikan. Para pencari seperti ini, kata Al-Ghazali, lebih mirip pedagang daripada ulama. Mereka menukar warisan kenabian—ilmu—demi keuntungan duniawi.
Motif kedua tampak ilmiah tetapi juga keliru: belajar demi membantah dan mengalahkan orang lain dalam perdebatan. Tipe pelajar seperti ini mencari tepuk tangan, bukan pemahaman; kemenangan, bukan hikmah. Kelas menjadi arena, pena menjadi pedang, pikiran menjadi perangkap bagi lawan intelektual. Al-Ghazali mencemooh keangkuhan akademik semacam ini, menegaskan bahwa ilmu yang dikejar untuk dominasi adalah ilmu yang kosong secara spiritual. Hati, katanya, harus memandu akal—bukan sebaliknya.
Motif ketiga adalah belajar karena rasa ingin tahu semata, tanpa tujuan selain mengetahui. Meskipun tampak tak berbahaya—karena rasa ingin tahu adalah akar dari pembelajaran—Al-Ghazali memperingatkan bahwa ilmu yang lepas dari akhlak bisa menjadi remeh. Pengetahuan tanpa aplikasi akan menjadi pengetahuan kosong. Belajar tapi tidak mengamalkan, katanya, seperti menanam benih tapi menolak menyiramnya. Rasa ingin tahu yang tak dipandu oleh nurani akan membawa pada stagnasi spiritual.
Motif keempat lahir dari rasa takut—bukan kepada Allah, tetapi kepada kemiskinan atau malu di depan orang. Para pelajar semacam ini menuntut ilmu agar tidak dianggap bodoh atau supaya bisa mendapat pekerjaan. Meskipun realistis, Al-Ghazali menganggap motif ini dangkal, tanpa kedalaman yang dibutuhkan untuk transformasi diri. Belajar, menurutnya, harus lahir dari harapan, bukan ketakutan. Jika tidak, jiwa digerakkan oleh kegelisahan, bukan oleh cinta pada kebenaran.
Akhirnya, Al-Ghazali menguraikan motif kelima dan satu-satunya yang terpuji: mencari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Ini adalah ilmu sebagai ibadah, sebagai perjalanan ke dalam diri. Penuntut ilmu dalam kategori ini tidak belajar untuk tampil, bersaing, atau mengesankan, tetapi untuk menyucikan hati dan memenuhi tujuan ilahiah. Tujuannya adalah mengamalkan apa yang ia pelajari, menjadi hamba, tetangga, dan insan yang lebih baik. Hanya niat seperti inilah yang layak dipuji, menurut Al-Ghazali.
Selain lima motif tadi, Al-Ghazali juga mengklasifikasikan orang berilmu berdasarkan bagaimana ilmu itu berdampak pada dirinya. Ia membagi para pemilik ilmu menjadi tiga golongan, bukan berdasarkan gelar, tetapi berdasarkan relasi mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Golongan pertama adalah mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya—ilmunya tidak mengubah perilaku. Mereka, kata Al-Ghazali, seperti lilin yang menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Mereka adalah paradoks: memandu orang lain dengan cahaya ilmu, tapi sendiri terhalang dari keselamatan.
Golongan kedua adalah mereka yang belajar dan mengamalkan apa yang telah mereka pelajari. Inilah model ideal menurut Al-Ghazali: ilmu yang berubah menjadi hikmah, lalu terwujud dalam amal saleh. Mereka adalah perwujudan sabda Nabi Muhammad SAW: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.” Mereka adalah pewaris para nabi—bukan karena nasab, tetapi karena akhlak. Ilmu mereka bukan sekadar hiasan, tapi menjadi lentera kerendahan hati.
Golongan ketiga adalah mereka yang tidak belajar dan tidak pula mengamalkan, yang sepenuhnya terkurung dalam kejahilan. Orang-orang ini bahkan belum memulai jalan pencarian ilmu, dan tetap tenggelam dalam kebodohan. Meskipun menyedihkan, mereka tidak seberbahaya golongan pertama—mereka yang tahu tetapi tidak peduli. Karena kebodohan masih bisa disembuhkan, tapi ilmu tanpa amal sering dipertahankan dengan kesombongan. Dalam pandangan Al-Ghazali, kebodohan adalah luka; ilmu tanpa amal adalah racun.
Mengetahui jalan tidak sama dengan menempuhnya, tegas Al-Ghazali. Karena itu, ia memberi sejumlah nasihat kepada mereka yang baru memulai perjalanan mencari ilmu. Pertama, ia menekankan pentingnya memurnikan niat sebelum membuka buku. Sebagus apapun topik atau guru, jika niat pelajar itu rusak, maka hasilnya pun akan cacat. Niat adalah tanah tempat benih ilmu tumbuh atau membusuk.
Kedua, Al-Ghazali menyarankan proses belajar yang perlahan dan mendalam—bukan terburu-buru menyelesaikan buku atau menghafal teks. Ia tidak menganjurkan pembelajaran yang dangkal, tetapi lebih memilih kedalaman daripada keluasan. Lebih baik memahami satu prinsip etika dan mengamalkannya, daripada tahu banyak hukum tapi tetap angkuh. Ilmu sejati menuntut kerendahan hati, bukan kecepatan. Belajar adalah ibadah, bukan perlombaan.
Ketiga, ia memperingatkan terhadap bahaya kesombongan, terutama ketika seseorang semakin dalam menuntut ilmu. Ilmu bisa memabukkan, dan bersamanya muncul godaan untuk merendahkan orang lain. Tapi pelajar yang tulus akan menyadari bahwa semakin banyak yang ia pelajari, semakin sadar ia akan kebodohannya sendiri. Di sanalah letak kerendahan hati, yang menurut Al-Ghazali adalah ciri utama seorang alim sejati. Ego adalah penghalang terbesar antara hati dan hikmah.
Keempat, ia mengingatkan agar pelajar selektif dalam memilih guru dan teman seperjalanan. Tidak semua yang memegang buku layak menjadi panutan, dan tidak semua yang bicara tentang ilmu benar-benar mengamalkannya. Penuntut ilmu harus mencari mereka yang perilakunya selaras dengan ucapannya, yang karakternya mencerminkan isi ajarannya. Ilmu, dalam hal ini, diserap tidak hanya dari teks, tapi juga dari pribadi. Jiwa belajar bukan hanya melalui kata, tapi juga melalui keteladanan.
Kelima, Al-Ghazali menekankan pentingnya muhasabah atau evaluasi diri secara rutin. Setiap hari, kata beliau, seorang pelajar harus bertanya: Apa yang sudah kupelajari, dan bagaimana aku berubah? Kebiasaan ini menjaga ilmu tetap hidup, tidak membeku menjadi sekadar informasi. Refleksi menjembatani antara teori dan praktik, antara akal dan hati. Dalam refleksi, ilmu menjadi cermin, bukan topeng.
Keenam, ia mengajak para pelajar untuk senantiasa bertaubat, terutama ketika mereka tergelincir. Pelajar tetap manusia, dan kesalahan adalah hal yang lumrah. Tapi tobat, menurut Al-Ghazali, bukanlah aib—melainkan api yang membakar kemunafikan dan melahirkan keikhlasan. Mengakui kesalahan bukan berarti kehilangan kehormatan, justru memperolehnya. Penuntut ilmu sejati bukanlah yang tanpa cela, tapi yang selalu kembali ke jalan-Nya.
Ketujuh, ia menasihati para pelajar untuk menjauhi cinta dunia, karena semakin banyak yang dikumpulkan dari dunia, semakin sempit ruang dalam hati untuk kebenaran. Ilmu yang dicari demi kemewahan akan menjadi rantai emas yang membelenggu ruh. Penuntut ilmu harus belajar hidup sederhana, agar jiwanya tetap ringan. Keterikatan pada dunia akan membutakan hati dari cahaya hakikat. Belajar harus menjadi bentuk pendakian, bukan pengumpulan harta.
Kedelapan, ia mengingatkan agar para pelajar senantiasa mengingat kematian—bukan sebagai obsesi muram, tetapi sebagai kompas makna. Jika hidup dilihat melalui lensa kefanaan, maka ilmu menjadi sesuatu yang mendesak dan penuh makna. Orang tidak belajar untuk mengesankan, tetapi untuk bersiap. Kubur adalah kelas yang sunyi, kata Al-Ghazali, di mana hanya ilmu yang diamalkan yang akan berbicara. Teori tidak berguna saat waktu habis.
Akhirnya, Al-Ghazali menutup risalahnya dengan harapan dan peringatan. Harapan—bagi siapa pun yang menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah; peringatan—bagi siapa pun yang menjadikannya alat meninggikan ego. Ilmu adalah cahaya, tapi di tangan yang salah, ia membakar. Menuntut ilmu adalah perjalanan suci. Dan setiap langkahnya harus hati-hati—dimulai dari hati.